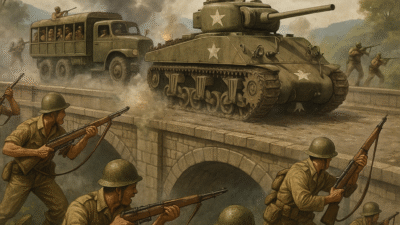TAN MALAKA: KISAH SEORANG FOUNDING FATHER YANG SENGAJA DIHILANGKAN DAN DILUPAKAN
Di antara kabut sejarah yang kerap kabur oleh debu waktu, ada satu nama yang menyala seperti bara di malam gelap – Tan Malaka.
Ia bukan sekadar tokoh, bukan pula sekadar pahlawan. Ia adalah puisi yang berjalan, revolusi yang bernapas dan kerinduan yang tak pernah pulang.
Lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897, ia tumbuh di antara lembah-lembah Minangkabau yang hijau, dikelilingi adat yang kokoh dan alam yang memesona.
Di sanalah, di antara gemericik sungai dan nyanyian saluang di senja, jiwa pemberontaknya mulai bersemi, bukan melawan alam, tapi melawan ketidakadilan yang datang dari seberang lautan.
Anak Minang yang Menjadi Badai
Tan Malaka, nama yang ia pilih sendiri, bukan warisan, adalah simbol perlawanan yang tak kenal kompromi. Tan berarti “tidak”, Malaka merujuk pada kota pelabuhan yang pernah jaya, lalu jatuh ke tangan penjajah.
Ia menolak takdir Malaka; ia menolak takdir jajahan. Ia adalah anak Minang yang membawa adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah ke dalam medan perjuangan global.
Ia belajar di Sekolah Kweekschool di Bukittinggi, lalu dikirim ke Belanda, di mana matanya terbuka lebar: dunia sedang berubah.
Revolusi Bolshevik di Rusia, nasionalisme di Asia, dan gelombang anti-imperialisme mengalir deras ke dalam jiwanya.
Di Belanda, ia bertemu dengan Marx, Lenin, dan api revolusi proletariat. Tapi Tan Malaka bukan pengekor.
Ia memadukan Marxisme dengan jiwa Indonesia dengan semangat gotong royong, dengan rasa keadilan ala nagari, dengan kearifan lokal yang tak bisa dihancurkan oleh teori Barat.
Ia menulis “Naar de Republiek Indonesia” (1925), buku yang menjadi cetak biru kemerdekaan Indonesia, ditulis jauh sebelum Soekarno-Hatta memproklamasikan.
Di dalamnya, ia menulis dengan tangan yang gemetar tapi hati yang teguh:
“Kemerdekaan bukan hadiah dari penjajah. Ia harus direbut, dituntut, diperjuangkan dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa.”
Sang Burung Api yang Terbang Sendirian
Tan Malaka adalah burung api yang terbang melawan angin. Ia diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Belanda, lalu ke Jerman, Rusia, Tiongkok, Filipina, Thailand, Burma dan hampir seluruh Asia Tenggara dan Eropa ia jejaki, bukan sebagai turis, tapi sebagai buronan, sebagai guru, sebagai penyuluh revolusi.
Di Moskow, ia menjadi wakil Indonesia di Komintern, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berani menentang Stalin ketika ia merasa garis perjuangan Indonesia tidak cocok dengan diktat Moskow. Ia diusir. Ia diasingkan. Tapi ia tak pernah menyerah.
Di Manila, ia menyamar sebagai guru Tionghoa bernama “Ibnu Said”. Di Bangkok, ia menulis buku revolusioner “Madilog” – Materialisme, Dialektika, Logika, sebuah mahakarya filsafat yang menggabungkan rasionalitas Barat dengan spiritualitas Timur.
Di sana, di antara lampu minyak dan kertas usang, ia menulis dengan tangan yang lelah, tapi mata yang masih menyala:
“Tanah air bukan hanya tempat lahir, tapi tempat di mana rakyatmu menderita dan kau punya kewajiban untuk membebaskannya.”
Kerinduan yang Tak Kunjung Pulang
Di balik jubah revolusioner, Tan Malaka adalah manusia yang rindu. Ia rindu pada rendang ibunya, pada gurauan kawan-kawan surau-nya, pada suara azan yang mengalun di lembah Suliki.
Dalam surat-suratnya yang tersebar, ia sering menulis tentang Minang, tentang sawah yang menguning, tentang rumah gadang yang teduh, tentang randai yang penuh semangat.
Tapi ia tahu, ia tak bisa pulang. Bukan karena takut, tapi karena tugasnya belum selesai.
“Aku rindu kampung halaman, tapi aku tak bisa pulang sebelum rakyatku merdeka. Biarlah rinduku jadi bahan bakar perjuangan.”
Ia pulang diam-diam tahun 1942, menyusup ke tanah air yang sedang diduduki Jepang. Ia menyusun jaringan bawah tanah, mendirikan Persatuan Perjuangan, menggalang kekuatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ia menolak kompromi.
Ia ingin kemerdekaan 100%, bukan setengah-setengah. Ia berseteru dengan Soekarno dan Hatta yang dianggapnya terlalu lunak. Ia dicap ekstremis. Ia diasingkan lagi, kali ini oleh bangsanya sendiri.
Akhir yang Sunyi, Tapi Tak Pernah Mati
Pada 21 Februari 1949, di sebuah desa kecil di Pegunungan Wilis, Jawa Timur, Tan Malaka dieksekusi diam-diam oleh pasukan Republik yang dia perjuangkan.
Ia ditembak tanpa pengadilan, tanpa proses, tanpa kehormatan. Jenazahnya disembunyikan. Namanya dihapus dari buku sejarah resmi. Tapi seperti api yang ditiup malah menyala lebih terang, semangatnya tak pernah mati.
Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, martir tanpa makam, penyair tanpa puisi yang dihafal.
Tapi di hati rakyat, ia abadi. Di hati Minang, ia adalah urang awak yang paling berani. Di hati Indonesia, ia adalah suara nurani yang menolak diam.
Epilog: Di Mana Kau, Tan Malaka?
Hari ini, ketika kita duduk di kafe atau roda tukang sate dengan secangkir teh atau kopi, ingatkah kita pada lelaki yang tidur di emperan stasiun demi revolusi?
Ketika kita mengeluh tentang harga BBM, ingatkah kita pada lelaki yang rela mati demi sejengkal tanah air? Ketika kita lupa sejarah, ingatkah kita bahwa Tan Malaka pernah menulis:
“Jika kau ingin merdeka, jangan menunggu izin. Bangkitlah. Lawan. Sekarang.”
Ia mungkin tak punya patung di istana, tak punya hari besar nasional, tak punya lagu wajib di sekolah.
Tapi di lembah-lembah Minang, di lorong-lorong Jakarta, di desa-desa Papua, semangatnya masih berbisik:
“Jangan pernah tunduk. Jangan pernah menyerah. Perjuangan belum selesai.”
Tan Malaka! Kau mungkin tak pulang ke Suliki, tapi Suliki tak pernah melupakanmu. Indonesia mungkin pernah mengkhianatimu, tapi sejarah akan selalu memelukmu.
Kau adalah burung api yang terbang melawan angin dan angin tak pernah bisa memadamkan api yang lahir dari cinta.
“Tan Malaka bukan hanya sekedar nama, ia adalah semangat. Ia adalah pertanyaan abadi: seberapa jauh kau rela berkorban untuk tanah airmu?”
Dan jika malam tiba, dan angin berhembus dari arah Bukit Barisan… dengarkanlah. Mungkin itu ia, sang burung api, yang masih bernyanyi untuk Indonesia… yang masih merindukan rumah.
Untuk Tan Malaka yang tak pernah mati, hanya menghilang sebentar, menunggu kita semua menyambutnya pulang dengan layak.
Referensi
- Tan Malaka. “Dari Penjara ke Penjara” (Autobiografi, 1948).
- Tan Malaka. “Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika” (1943).
- Tan Malaka. “Naar de Republiek Indonesia” (1925).
- Harry A. Poeze. “Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik” (4 Jilid, 2007-2009) – riset monumental.
- Asvi Warman Adam. “Tan Malaka: Kegelisahan Seorang Revolusioner” (Esai Historis, 2011).
- Wisran Hadi. “Tan Malaka dalam Sastra Minang” – kajian sastra daerah.
- Pramoedya Ananta Toer. “Sang Pemula” – novel biografis tentang Tirto Adhi Soerjo, tapi banyak menyentuh semangat zaman Tan Malaka.
- Majalah “Star Weekly” (1950-an) – tulisan-tulisan awal tentang Tan Malaka pasca-kematiannya.
- Film “Guru Bangsa: Tjokroaminoto” (2015)” – menyentuh sedikit peran Tan Malaka dalam gerakan pergerakan.
- Pidato-pidato Tan Malaka dalam arsip Komintern, Moskow – tersedia dalam terjemahan Poeze.