Kerjasama Pemberitaan/Iklan:
Contact Person: (0878-9163-1225). e-mail: bewarasiliwangi9@gmail.com
EPISODE: NIL, SUNGAI YANG MENGALIRKAN RAGAM CERITA
Kairo, Mesir – Musim Semi 1326 M
Langit Kairo pagi itu berwarna madu. Di tepi Sungai Nil yang mengalir perlahan, kabut tipis menari-nari seperti jilbab para bidadari.
Di antara deretan pohon palem dan ladang gandum, seorang pemuda berjubah cokelat tua berdiri diam, memandang jauh ke arah cakrawala.
Matanya yang tajam, seperti pedang yang diasah oleh angin gurun, menatap menara Masjid Ibn Tulun, bangunan batu yang menjulang seperti penjaga abadi dari zaman Firaun hingga Islam.
Ia adalah Muhammad Ibnu Battuta, putra Fez yang telah meninggalkan rumah dengan hanya sebuah mimpi: melihat dunia, menuntut ilmu, dan menemukan wajah Tuhan di setiap sudut bumi.
Setelah delapan bulan menyeberangi gurun Sahara, melalui Tlemcen, Tunis, dan Tripoli, ia akhirnya tiba di Kairo yang disebut para ulama sebagai “Umm al-Dunya” Ibu dari Segala Kota.
Gerbang Menuju Ilmu
Kairo bukan hanya kota. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Pasar-pasarnya ramai oleh pedagang dari Andalusia hingga India.
Perpustakaan-perpustakaannya penuh kitab berusia ratusan tahun. Dan di jantungnya berdiri “Al-Azhar, mercusuar ilmu yang cahayanya menembus malam kebodohan.
Ibnu Battuta masuk ke kota dengan kaki yang lelah, tapi hati yang lapar. Ia tidak mencari emas, bukan pula kekuasaan, ia mencari kebenaran.
Di suatu sore, di teras rumah seorang ulama tua bernama Syekh Abu al-Hasan al-Misri, Ibnu Battuta duduk bersila, mendengarkan ceramah tentang adab musafir—etika pengembara.
“Wahai pemuda dari Maghribi,” kata sang syekh, suaranya dalam seperti gemuruh sungai bawah tanah, “Perjalananmu bukan hanya dari Fez ke Mekkah. Ini adalah perjalanan dari ketidaktahuan menuju makrifat. Dan Kairo adalah gerbang pertamamu ke dunia yang lebih besar.”
Ibnu Battuta menunduk. “Aku datang dengan tangan kosong, wahai Syekh. Tapi aku membawa hati yang ingin belajar.”
Syekh itu tersenyum. “Itu lebih dari cukup.”
Hari-Hari di Bawah Bayang Nil
Selama tiga bulan, Ibnu Battuta hidup seperti sungai, tenang, tapi tak pernah berhenti mengalir.
Pagi itu ia pergi ke Masjid Amr ibn al-As, masjid pertama di Afrika, berdoa, lalu duduk di sudut masjid mendengarkan para ulama berdebat tentang fiqih dan tafsir.
Siangnya ia berjalan ke Piramida Giza yang menjulang seperti mimpi raksasa dari zaman purba. Di sana, ia menulis dalam hati:
“Batu-batu ini lebih tua dari kitab-kitab kami, tapi mereka diam. Hanya manusia yang bisa bercerita. Maka aku harus bercerita.”
Sore harinya ia pergi menyewa kamar kecil di kawasan Bayn al-Qasrayn, dekat pasar Khan al-Khalili. Di sana, ia berteman dengan seorang penulis naskah, Yahya al-Andalusi, yang membantunya menyalin kutipan dari kitab al-Muwatta karya Malik.
Malam harinya ia duduk di tepi Nil, menatap bulan yang terpantul di air seperti cincin emas. Kadang, ia menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena kerinduan.
Ia merindukan ibunya yang duduk di teras rumah, merajut selendang, menunggu kabar anaknya.
Pertemuan dengan Sang Nadi Dunia
Suatu malam, saat ia duduk di dermaga, seorang nelayan tua mendekat, membawa ikan segar dan senyum yang penuh keriput.
“Kau bukan orang Mesir, ya?” tanya si nelayan.
“Tidak. Aku dari Fez.”
Nelayan itu tertawa. “Fez? Aku pernah dengar nama itu dari pedagang sutra. Tapi kau lebih mirip anak sungai, mengalir jauh dari sumbermu.”
Ibnu Battuta terdiam. “Aku merasa seperti sungai yang tersesat.”
“Tidak ada sungai yang tersesat,” kata si nelayan. “Semua mengalir ke laut. Seperti manusia pasti semua kembali ke Yang Esa. Tapi jalannya berbeda-beda. Kaulah yang memilih jalanmu.”
Malam itu, Ibnu Battuta menulis di dalam hati:
“Nil mengajarku: keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah terus mengalir, meski arusnya deras, meski batu menghalang.”
Keberangkatan Menuju Mekkah
Pada musim panas 1326, Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekkah. Ia bergabung dengan karavan haji yang berangkat dari Kairo menuju Hijaz. Sebelum berangkat, Syekh Abu al-Hasan memberinya sebuah kantong kecil berisi tanah dari makam Imam Syafi’i.
“Bawa ini,” katanya. “Agar kau tahu: ilmu itu tumbuh dari tanah, seperti pohon. Dan kau adalah benih yang harus ditanam di tanah-tanah asing.”
Di gerbang kota, Ibnu Battuta menoleh sekali lagi ke arah Kairo. Kota itu berkilau di bawah matahari, seperti permata yang dihiasi oleh tangan Tuhan.
Ia berbisik, “Terima kasih, Ibu Dunia. Kau telah memberiku air, ilmu, dan pelajaran pertama tentang keberanian.”
Lalu ia melangkah, kaki di atas pasir, hati di atas iman.
Di tengah dunia yang gemerlap, Ibnu Battuta tidak mencari kemasyhuran. Ia mencari makna. Dan di Kairo, ia menemukan bahwa keberanian bukan hanya bertahan di gurun atau menghadapi bajak laut—tapi bertahan mencintai ilmu, meski jauh dari rumah.
Karena baginya, setiap kota adalah guru. Setiap sungai adalah doa. Dan setiap langkah, adalah ibadah.
“Aku pergi untuk melihat dunia. Tapi dunia mengajarkanku untuk melihat diriku.”
Ibnu Battuta (dalam bayang-bayang Nil, 1326)
Catatan Historis:
Tahun kedatangan: 1326 M (setelah menyeberangi Afrika Utara).
Durasi tinggal di Kairo: Sekitar 3–4 bulan sebelum melanjutkan haji.
Tempat penting dikunjungi: Masjid Amr ibn al-As, Al-Azhar, Piramida Giza, pasar Khan al-Khalili.
Konteks sejarah: Kairo saat itu berada di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk yang menjadikannya pusat ilmu, perdagangan, dan seni Islam.
Sumber utama: “Rihlah Ibn Battuta” ditulis oleh Ibnu Juzayy atas dictasi Ibnu Battuta (1354 M).











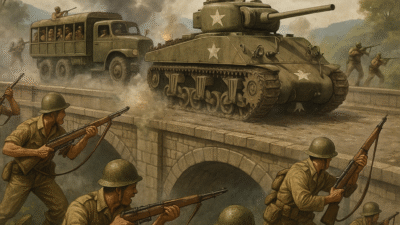


https://shorturl.fm/tqNyY
Mantaaapp