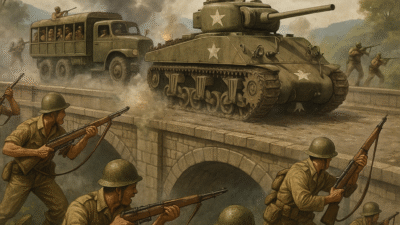SANG PENYELAMAT DI UJUNG JURANG: UGA WANGSIT SILIWANGI DAN NUSANTARA YANG HAMPIR LENYAP
Langit merah menangis penuh debu dan abu. Bumi retak oleh nafsu serakah tak kunjung puas.
Lautan bergelora tanpa nakhoda. Dan di antara keheningan yang ramai berteriak – ia datang…
bukan dengan kereta emas, bukan dengan panji perang, tapi dengan kaki telanjang yang mencium tanah dan hati yang tegar walaupun lelah.
Ia adalah yang diramalkan – sosok dari uga wangsit Prabu Siliwangi, raja bijak yang memilih menghilang ke dalam kabut zaman, meninggalkan pesan-pesan gaib yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa bersih yang masih percaya pada keadilan, pada kebenaran dan cinta tanpa syarat kepada Ibu Pertiwi.
“Kelak, saat Nusantara terguncang di tepi jurang kebinasaan, saat kebohongan dan kepalsuan merajalela berkuasa, saat pengkhianatan jadi jalan kehidupan, saat anak bangsa saling tikam dengan lidah dan senjata, saat harta dan jabatan dijunjung tinggi di atas kepala, saat kehormatan dihempas dan dihinakan serta diinjak-injak tanpa belas kasihan…
Ia muncul…
dari tempat yang tak disangka: pinggiran, hutan, gunung, atau bahkan tanah tak bertuan. Ia tak berjubah, tak bertakhta, tapi membawa “kawasa tanpa paksa” – kekuatan tanpa paksaan.”
Ia bukan mesias yang ditunggu dengan sorak dan bunga penyambutan. Ia adalah orang biasa yang dipilih oleh waktu, ditetapkan oleh zaman dan diangkat oleh takdir kuasa langit.
Mungkin seorang petani yang tahu bahasa angin dan bisikan musim. Mungkin seorang nelayan yang mengerti ratapan ombak dan teriakan badai.
Mungkin seorang guru yang mengajarkan kehormatan dan kejujuran di antara debu dan deru kebohongan serta kepalsuan.
Atau seorang Budak Angon, sang gembala sunyi yang serulingnya mampu menenangkan badai di hati manusia.
Ia tak memerlukan istana – karena kekuasaannya adalah keikhlasan. Ia tak butuh pengikut karena misinya adalah membangunkan bukan menguasai.
Wahyu keprabon telah melekat pada dirinya, Sabda Pandita Ratu adalah ucapannya.
Sejatinya dia adalah pewaris harta dua tahta: Harta Padjadjaran yang ikut menghilang bersama sang Raja Agung yang ngahyang – tahta serta istana Sunda Galuh yang kini tinggal catatan nama.
“Ia datang saat semua ajaran nabi diabaikan, saat semua raja lupa janji, saat kiai leungit aji, saat Pandita ilang komara saat semua takut bicara.
Ia datang saat bangsa lupa jati dirinya – semua terbakar dan terbungkus oleh hawa nafsu serakah dan amarah.
Mereka lupa bahwa mereka lahir dari samudra yang damai, dari gunung yang bijak, dari rimba yang penuh rahasia tapi saling menjaga.
Ia berjalan menyusuri desa-desa yang terlupakan, kota-kota yang terabaikan, nusa yang terbelah oleh kebencian.
Di setiap langkahnya, ia menanam benih-benih kesadaran: bahwa kekayaan sejati bukan di materi, tapi di hati – bahwa kekuatan sejati bukan di senjata, tapi di kebersamaan, bahwa kemuliaan sejati bukan di gelar tapi di pengabdian.
Dan ketika ia tiba di istana pusat keserakahan dan kerusakan, di ibu kota yang gemerlap tapi hampa, di parlemen yang ramai tapi sepi hati nurani ia tak berteriak.
Ia duduk. Ia diam. Dan diamnya lebih mengguncang daripada dentuman meriam. Karena dalam diamnya, ia memantulkan wajah-wajah mereka yang lupa: Siapa kamu? Untuk siapa kamu berkuasa? Apa artinya semua ini, jika rakyatmu menangis?
Ia tak menghancurkan sistem. Ia mengubah hati. Dan ketika hati berubah sistem pun runtuh dengan sendirinya, seperti daun tua yang kering dan jatuh ditiup angin penghakiman semesta yang telah muak.
Lambat laun, yang tadinya benci mulai berbicara. Yang tadinya curiga mulai berjabat tangan. Yang tadinya korup mulai menangis – bukan karena takut hukuman, tapi karena sadar telah mengkhianati tanah kelahirannya.
Nusantara, yang hampir jatuh ke jurang kehancuran, mulai menemukan pijakannya kembali, bukan karena kekuatan militer atau kecerdasan ekonomi, tapi karena kekuatan jiwa yang dibawa oleh Sang Penyelamat.
Ia tak ingin diingat sebagai pahlawan. Ia hanya ingin Nusantara kembali menjadi rumah – tempat di mana anak-anak yatim bisa tertawa tanpa khawatir masa depan, di mana orang miskin bisa tidur tanpa lapar, di mana alam dan manusia hidup dalam harmoni purba yang suci.
Maka, jika kau bertanya – Di manakah Sang Penyelamat itu? Dengarkan… Ia mungkin sedang duduk di warung pinggir jalan yang tak dikenal – menyeruput kopi pahit sambil menghisap sebatang rokok.
Ia mungkin sedang menulis puisi di buku lusuh, atau mengajar anak-anak membaca di bawah pohon kenanga.
Ia mungkin adalah dirimu. Ya. Dirimu. Yang masih percaya. Yang masih berani mencintai tanpa syarat. Yang masih berdiri meski dunia di sekelilingmu mulai runtuh.
Karena Uga Wangsit Siliwangi bukan ramalan takdir yang diam, tapi panggilan jiwa bagi siapa saja yang mau bangkit, menjadi cahaya di ujung jurang.
Epilog
“Maka, wahai Nusantara yang sakit dan letih janganlah putus asa. Di ujung jurang, selalu ada tangan yang terulur. Bukan dari langit, tapi dari tanah.
Bukan dewa, tapi manusia biasa yang dipaksa memilih menjadi luar biasa, demi cinta yang tak pernah mati: cinta kepada tanah airnya.”
Dan di sanalah, Uga Wangsit Siliwangi bukan sekadar mitos… tapi cermin jiwa yang menanti kau untuk memenuhinya.
“Tereh nincak mangsa jeung waktuna Geutih Siliwangi nyepeung kawasa mingpin bangsa jeung nagara, Nanjeurkeun Kaadilan Mawa Kamakmuran nu Walatra ka sakabeh Rahayatna – Biidznillah Kersaning Pangeran”
“Hampir tiba masa dan waktunya Geutih Siliwangi memegang kuasa memimpin bangsa dan negara, Menegakan Keadilan dan Membawa Kemakmuran yang merata ke Seluruh Rakyatnya – Biidznillah Kersaning Pangeran”