UGA WANGSIT SILIWANGI: BUDAK ANGON MENUNGGU KETETAPAN LANGIT
Di kaki gunung yang sunyi, di antara tarian ilalang dan bisikan angin yang membawa debu zaman, duduk seorang budak angon – gembala yang tak bernama dalam catatan sejarah, namun jiwanya menyala seperti bara dalam abu.
Ia tidak menggembalakan kerbau dan domba di padang rumput, tapi ia seorang penggembala manusia di padang kesedihan bangsa yang nyaris kehilangan jati diri dan nurani.
Matanya telah lelah dan bosan menyaksikan langit yang semakin hitam pekat, bukan karena mendung, melainkan karena asap pengkhianatan yang mengepul dari istana-istana palsu, tempat para penguasa jahat duduk di atas takhta yang dibangun dari cucuran keringat penderitaan rakyat serta tetesan darah para pejuang sejati.
Ia tahu, ia harus tahu karena wangsit itu telah datang dalam mimpi-mimpi sunyi, dalam bisikan batu karang, dalam nyanyian burung hantu di malam purnama.
Uga Wangsit Prabu Siliwangi berbisik: “Nanti akan datang masa gelap, ketika negeri ini dikuasai oleh para durjana yang menyamar sebagai pemimpin, didukung disanjung para pengkhianat yang berpakaian kebajikan, dibela dijaga oleh para penjahat yang memegang kitab suci di tangan kanan, namun menghunus pedang penindasan serta pengkhianatan di tangan kiri.”
Dan di sanalah sang budak angon menunggu. Bukan karena takut, bukan karena lemah, melainkan karena waktu belum berpihak.
Sejatinya ia adalah Satria Piningit – kesatria yang terpaksa dan dipaksa mengasingkan diri tersembunyi, bukan untuk lari, tapi untuk menjaga nyala dan bara semangat nusantara yang hampir padam.
Ia menunggu saat ketika kebenaran tak lagi bisa dibungkam oleh emas, ketika kepalsuan mulai ditampakkan wujud aslinya, ketika penindasan dan pengkhianatan jelas dipertontonkan, ketika rakyat bangkit dari tidur panjangnya – dan ketika bumi ini sendiri menuntut keadilan dan meminta tumbal darah atas nafsu serakah manusia.
Dalam kesunyiannya, ia mencintai tanah air ini dengan cara yang tak pernah dimengerti oleh para penguasa: dengan kesabaran yang mengalir seperti sungai, dengan kerendahan hati yang menembus batu, dan dengan cinta yang tak pernah meminta balas.
Ia mencintai seperti padi mencintai hujan – diam, tulus, dan siap memberi meski tak pernah dipuji.
Namun, di balik senyumnya yang samar, ada pedang tajam yang terus diasah dalam diam.
Di balik senandungnya yang lembut, ada nyanyian dan teriakan lantang membahana disertai taluan genderang perang yang siap melumat dan membinasakan nafsu angkara serakah manusia.
Ia tahu, ketika sangkakala keadilan akhirnya ditiup, ia tak akan datang dengan gemerlap, tapi dengan kepastian.
Ia tak akan datang sebagai raja, tapi sebagai the liberator – sang pembebas, mengembalikan yang hilang, menyatukan yang tercerai-berai, dan membersihkan negeri ini dari noda-noda pekat kehinaan dan pengkhianatan yang telah menggerogoti jiwa bangsa.
Hingga hari itu tiba, ia tetap menjadi budak angon yang sederhana, setia, dan penuh rahasia. Karena kadang, pahlawan sejati tak memakai jubah emas, melainkan kain compang-camping yang basah oleh embun pagi.
Dan cintanya pada tanah air bukanlah cinta yang riuh, melainkan cinta yang rela menunggu dalam sunyi, dalam rasa rindu, bahkan dalam penderitaan yang seolah tak berujung – karena ia yakin bahwa kegelapan takkan abadi.
“Wahai Nusantara yang muak dan letih…Jangan kau putus asa. Karena di suatu padang, di antara kerbau dan langit senja, ada seorang gembala yang sedang menunggu panggilan takdir.
Saksikanlah! Ketika genderang dan tarian perang telah diteriakan dengan lantang – Ia akan datang dengan pedang pembalasan, membawa restu dan ketetapan langit.”








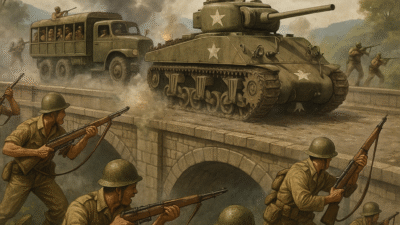





https://shorturl.fm/bCdM5
https://shorturl.fm/mJEii