ZAMAN NORMAL DI BAWAH BAYANG-BAYANG KOLONIAL BELANDA: SEBUAH RENUNGAN
Di bawah langit Nusantara yang biru keemasan, ketika angin laut membawa aroma garam dan kenangan, ada masa yang disebut zaman normal.
Sebuah frasa yang terdengar tenang, hampir damai, namun menyimpan ribuan desah, tangis dan bisikan pemberontakan yang tersembunyi di balik senyum patuh.
Zaman ini bukanlah zaman tanpa gejolak, melainkan zaman ketika gejolak itu dipaksa bersembunyi, berpura-pura tenang, seperti sungai yang jernih permukaannya namun deras arus bawahnya.
Definisi Zaman Normal dalam Konteks Kolonial
Secara historis, istilah zaman normal kerap digunakan untuk merujuk pada periode setelah masa-masa krisis atau pemberontakan besar ketika pemerintah kolonial Belanda berhasil memulihkan ketertiban, menekan perlawanan, dan memperkuat kontrol birokrasi serta militer.
Ini adalah masa ketika ketertiban kolonial tampak berjalan lancar, seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah rakyat menerima takdirnya dengan ikhlas.
Namun, dalam gaya sastra dan romantisme, zaman normal adalah ironi yang manis tapi pahit: sebuah topeng emas yang menutupi wajah penuh luka. Seperti puisi Chairil Anwar yang menulis, “Aku tetap menulis, meski kau membungkam mulutku dengan tanah,”
Di zaman normal, pena dan mulut boleh jadi terbungkam, tapi jiwa tetap menulis, tetap berbisik, tetap memberontak dalam diam.
“Normalitas adalah keheningan yang dipaksakan. Di baliknya, ribuan hati berdetak dengan irama pemberontakan yang tak terucap.”
Romantisme dalam Keseharian Zaman Normal
Bayangkan pagi yang cerah di Batavia, 1920-an. Lonceng gereja berdentang lembut, sepeda-sepeda Belanda melintas di jalan berbatu, sementara di belakangnya, para inlander berjalan menunduk, membawa beban hidup yang tak terlihat oleh mata tuan.
Di kebun teh Priangan, gadis-gadis Sunda memetik daun dengan jari-jari lentik, sementara di kantor pemerintahan, para priyayi berdasi mengetik laporan dengan mesin ketik tua, menuruti perintah atasannya yang berkulit pucat.
Inilah romantisme zaman normal: keindahan yang tragis, seperti lukisan Raden Saleh yang memperlihatkan keagungan alam dan manusia, namun selalu ada bayangan gelap di sudutnya – simbol penjajahan, ketidakadilan, dan kerinduan akan kebebasan.
“Di antara bunga melati dan kopi panas, kami menyembunyikan dendam. Di balik senyum pelayan, ada doa yang tak terucap: ‘Tuhan, kapan kami merdeka?”
Struktur Kekuasaan dan Ilusi Ketertiban
Zaman normal bukanlah kebetulan. Ia diciptakan dengan sengaja oleh pemerintah kolonial melalui:
- Politik Etis (1901–1942) yang memberi ilusi kemajuan berupa pembangunan sekolah, irigasi, jalan kereta api. Tapi semua itu untuk memperkuat eksploitasi, bukan membebaskan.
- Sistem Birokrasi dan Polisi Kolonial yang mengawasi setiap gerak-gerik, setiap surat kabar, setiap pertemuan.
- Pembagian Kelas Sosial yang Kaku dalam bentuk Europeesche, Vreemde Oosterlingen dan Inlander telah menciptakan hierarki yang tak tergoyahkan, seolah-olah alamiah, padahal dibangun oleh kekuasaan.
Namun, di balik struktur yang kaku itu, tumbuh benih-benih perlawanan. Di sekolah-sekolah HIS dan STOVIA, anak-anak muda mulai membaca Marx, Rousseau, dan Multatuli.
Mereka mulai bertanya: “Mengapa kita disebut bodoh, padahal kita yang membangun jembatan ini? Mengapa kita disebut rendah, padahal kita yang menanam padi yang kau makan?”
“Kami belajar membaca, lalu membaca ketidakadilan. Kami belajar menulis, lalu menulis harapan. Zaman normal? Tidak. Ini adalah masa persiapan badai.”
Suara-Suara yang Menolak Normalitas
Di tengah “ketenangan” itu, muncul suara-suara yang menolak definisi normal. Mereka adalah para penyair, wartawan, guru, dan aktivis yang menggunakan pena sebagai senjata.
- Multatuli (Eduard Douwes Dekker) dalam “Max Havelaar” (1860), menelanjangi kekejaman sistem tanam paksa dengan gaya satir yang penuh ironi dan cinta terhadap rakyat kecil.
- Tirto Adhi Soerjo sang pelopor pers perlawanan, yang menulis di Medan Prijaji, menolak diam meski diasingkan.
- Sutan Sjahrir yang dalam “Perjuangan Kita” (1945, tapi berakar dari zaman normal) menulis: “Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hak yang harus direbut.”
Dan jangan lupakan para perempuan seperti Kartini, yang dalam surat-suratnya merindukan dunia di mana perempuan bisa berpikir bebas
Dewi Sartika dari Bandung yang diam-diam mendirikan sekolah di tengah tekanan adat dan kolonial.
“Mereka menyebut ini normal. Tapi kami, yang menatap bulan dari balik jeruji, tahu: normal adalah penjara tanpa dinding.”
Normalitas sebagai Panggung Sandiwara
Zaman normal di bawah Belanda adalah panggung sandiwara kolosal. Di atas panggung, semua tampak rapi, tertib, dan harmonis.
Tapi di balik layar, air mata mengalir, darah menetes, dan mimpi-mimpi kebebasan disusun dalam rapat-rapat gelap, dalam puisi-puisi samar, dalam lagu-lagu daerah yang penuh kode perlawanan.
Romantisme zaman ini bukan pada keindahan kolonialnya, tapi pada kegigihan manusia-manusia kecil yang menolak menyerah.
Mereka adalah pahlawan tanpa medali, penyair tanpa panggung, guru tanpa gaji yang tetap menanam benih merdeka di tanah yang diinjak-injak penjajah.
“Jika kau bertanya, apa arti zaman normal? Ia adalah waktu ketika kami belajar diam, tapi tak pernah berhenti bermimpi. Ketika kami dipaksa tersenyum, tapi hati kami menulis puisi perlawanan. Ketika mereka bilang semua baik-baik saja, kami tahu: badai dahsyat sedang disiapkan.”
Epilog
Zaman normal bukanlah akhir dari cerita, melainkan jeda sebelum orkestra perlawanan dimainkan.
Dan ketika orkestra itu dimainkan, langit pun ikut bernyanyi menyambut fajar kemerdekaan yang tak bisa lagi ditahan oleh tirani mana pun.
Ditulis dengan pena yang direndam dalam tinta sejarah dan hati yang berdetak bersama jiwa-jiwa pejuang masa lalu.
Referensi
- Pramoedya Ananta Toer – “Bumi Manusia” (1980), “Rumah Kaca” (1988)
- Multatuli – “Max Havelaar” (1860)
- Rudolf Mrázek – “Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony” (2002)
- Robert Van Niel – “The Emergence of the Modern Indonesian Elite” (1960).
- Sartono Kartodirdjo – “Protest Movements in Rural Java” (1973)
- Armijn Pane – Belenggu” (1940)
- Soekarno” – “Indonesia Menggugat” (1926)
- Surat-surat Kartini” – “Habis Gelap Terbitlah Terang” (1911, diedit oleh J.H. Abendanon).
- George McTurnan Kahin – “Nationalism and Revolution in Indonesia” (1952)
- A. Teeuw – “Modern Indonesian Literature” (1967). Analisis sastra zaman kolonial








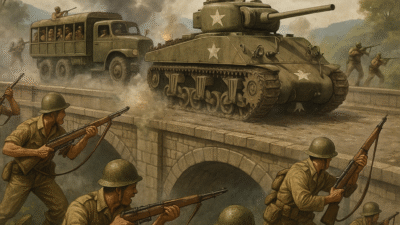





https://shorturl.fm/kaXl7
https://shorturl.fm/lZj2p